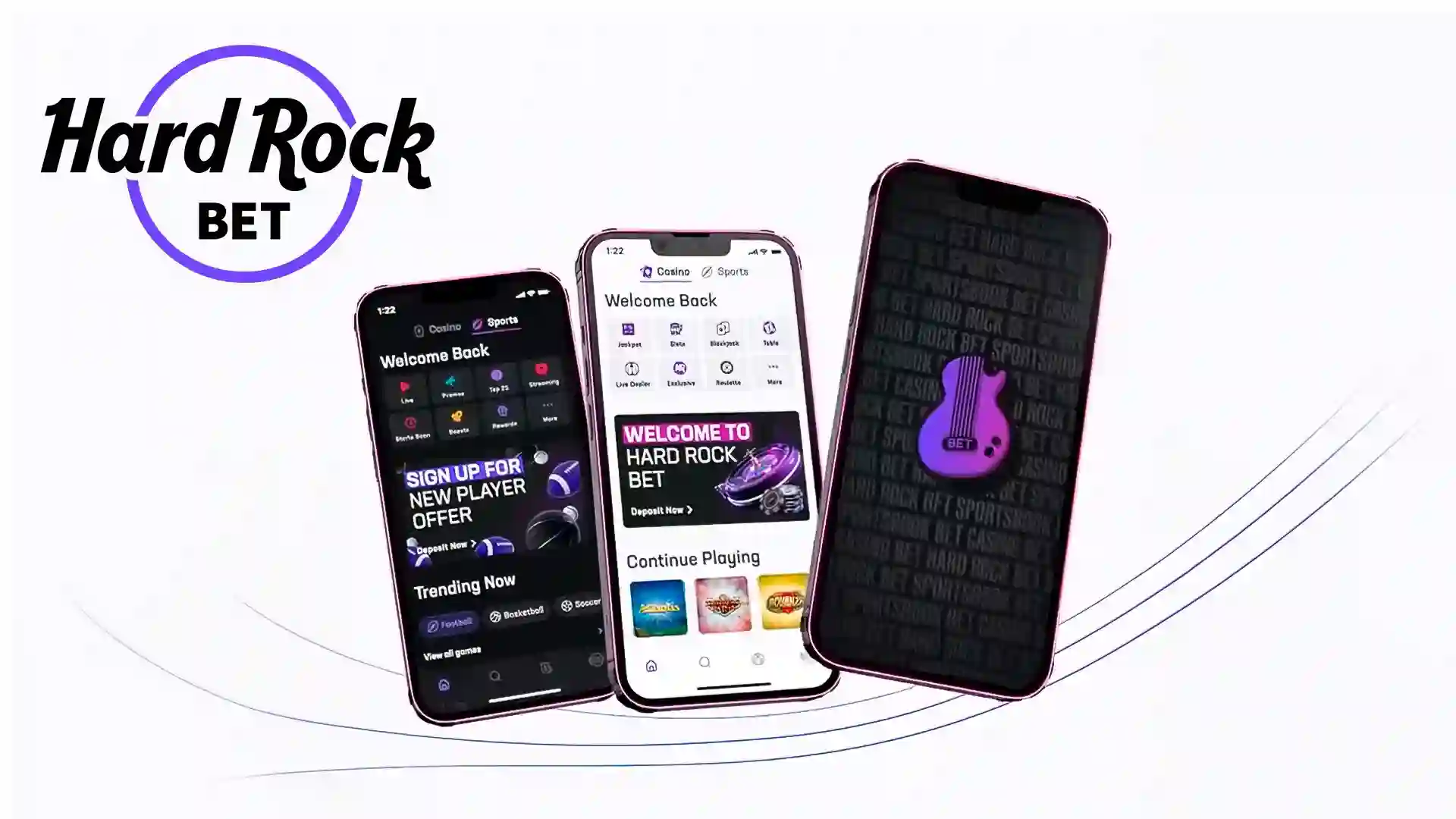Indonesia, dengan keragaman hayati dan bentang alamnya, kerap menyimpan kisah dualitas dalam setiap jejak langkah manusianya. Gunung Rinjani di Lombok, Nusa Tenggara Barat, dalam beberapa tahun terakhir bukan hanya menjadi magnet bagi pecinta alam, pencinta pendakian, ataupun fotografer lanskap. Ia kini juga berada di persimpangan kontroversi antara euforia pariwisata, ketegangan sosial, dan kepercayaan lokal soal misteri dunia gaib yang masih berdenyut kuat di masyarakat sekitar.
Rinjani dalam Lintasan Data dan Realitas Ekonomi
Tinggi 3.726 meter di atas permukaan laut, Rinjani menjadi gunung tertinggi kedua di Indonesia. Statusnya sebagai salah satu destinasi wisata unggulan telah mendongkrak sektor ekonomi lokal. Menurut data Badan Pusat Statistik NTB, kunjungan wisatawan ke kawasan Rinjani melonjak signifikan pasca-pandemi, mencapai lebih dari 120 ribu per tahun pada 2024. Sektor homestay, jasa porter, hingga UMKM setempat—seperti produsen madu hutan dan kerajinan tangan—tumbuh pesat, memberikan penghidupan untuk ribuan warga.
Namun, realitas di lapangan tak seindah poster promosi tur wisata. Lonjakan pendaki, terutama pascaliburnya pandemi, memperburuk masalah sampah dan erosi jalur pendakian. Laporan WALHI NTB menyebutkan lebih dari 15 ton sampah non-organik dikumpulkan hanya dalam satu musim pendakian tahun 2023. Kekhawatiran publik pun menguat, terutama dari pemangku adat dan LSM yang menyoroti lemahnya penegakan regulasi lingkungan.
Sisi Lain: Nilai Sakral dan Misteri Dunia Gaib
Tak dapat dimungkiri, bagi sebagian besar masyarakat adat Sasak dan Bali yang mendiami kaki Rinjani, gunung ini bukan semata lanskap hidup atau sumber ekonomi—melainkan juga pusat spritualitas dan misteri gaib. Ada kepercayaan yang turun-temurun, bahwa Rinjani adalah “pusat dunia” atau makam Dewi Anjani, sosok sakti penjaga alam.
“Bagi kami, mendaki Rinjani bukan hanya soal keberanian fisik. Harus ada izin batin dan etika yang dijaga. Banyak yang sakit, hilang, atau mendapat musibah karena tidak menghormati tempat ini,” ujar Pak Lalu Abdillah, juru kunci sekaligus tetua adat Sembalun, dalam wawancara dengan Kompas (2024). Pengalaman mistis seperti suara azan misterius, penampakan makhluk tak kasat mata, hingga kisah pendaki yang tersesat muncul hampir di setiap musim pendakian. Fenomena ini pun lantas tumbuh subur sebagai bagian dari narasi lokal dan kerap digunakan sebagai pengingat sekaligus kontrol sosial.
Pada satu sisi, kisah misteri ini memang tak lepas dari motif konservasi: menanamkan rasa takut agar pendaki menjaga sopan santun dan melindungi alam. Namun, di sisi lain, belief system ini kerap menjadi batu sandungan bagi modernisasi kebijakan, seperti pembatasan kunjungan atau zonasi konservasi, yang ditolak sebagian warga dengan alasan bertentangan dengan kearifan lokal.
Studi Kasus: Hilangnya Pendaki dan Respons Pemerintah
Satu kasus yang merefleksikan tegangan ini adalah hilangnya tiga pendaki asal Surabaya di jalur Senaru pada Juli 2022. Setelah operasi SAR berkepanjangan, dua diantaranya ditemukan dalam kondisi selamat, sementara satu lagi tidak pernah ditemukan. Narasi yang berkembang, kejadian ini diyakini sebagai bentuk “kemarahan” penunggu Rinjani akibat perbuatan sembrono korban di pos 3. Meski aparat telah menegaskan dominasi faktor cuaca dan navigasi yang buruk—bukan aspek supranatural—perdebatan publik mengenai “penghuni gaib” Rinjani tetap lahir dan menyoroti irisan antara sains dan kepercayaan lokal.
Pemerintah daerah dan Balai Taman Nasional pun mengalami dilema. Kebutuhan menggenjot kunjungan wisatawan harus diimbangi edukasi soal etika dan keselamatan, tanpa mempermainkan narasi mistis secukupnya agar pesan konservasi tetap menggema. “Kami kerap diedukasi agar tidak membuang sampah, menjaga perilaku, dan menghormati site tertentu. Tapi pesan-pesan itu jadi setengah gaung jika hanya diberi sentuhan mistis tanpa data atau fakta lapangan,” ujar Rudi Hartono, ketua komunitas porters di Sembalun.
Potret Nyata di Lapangan: Antara Ritual dan Rezim Bisnis
Kini, setiap musim pendakian, ritual selamatan tetap digelar oleh pemuka adat. Bunga, ayam, dan sesaji air zam-zam dialirkan demi keselamatan para penjelajah gunung. Namun, di sisi lain, para pengelola jasa pendakian, khususnya travel agent dari luar NTB, mulai memanfaatkan narasi mistis tersebut sebagai nilai jual paket wisata. Fenomena komodifikasi misteri—alih-alih mengenalkan sejarah dan budaya secara utuh—tentu menyulut protes dari tokoh lokal yang menganggap praktik itu sekadar memburu profit tanpa empati kultural.
Pakar antropologi dari Universitas Mataram, Dr. Riska Muliyani, dalam diskusi publik baru-baru ini menegaskan, “Transformasi makna gunung dari entitas sakral ke komoditas wisata mengandung implikasi sosial; bisa memperkuat identitas atau malah menimbulkan alienasi kultural.” Ketegangan antara komodifikasi, pelestarian, dan kearifan lokal inilah yang membuat isu Rinjani jauh lebih kompleks dari sekadar masalah kebersihan atau promosi pariwisata.
Refleksi dan Tantangan Masa Depan
Menyadari potensi dan tantangan yang mengelilingi Gunung Rinjani, dibutuhkan kolaborasi nyata semua pihak: regulasi yang lebih berani dan transparan, pendidikan ekowisata yang berbasis riset, serta pengakuan serius terhadap kontribusi dan pengetahuan lokal. Kunci besarnya ada pada upaya mempertemukan sains lingkungan dengan narasi kultural, tanpa saling menegasikan peran satu sama lain.
Pada akhirnya, Rinjani seharusnya tidak hanya dipandang sebagai arena backpacker berburu sensasi atau medan kontestasi kekuatan gaib, tetapi sebagai ekosistem sosial-budaya yang memerlukan perlakuan adil, progresif, dan reflektif dari seluruh pemangku kepentingan.
Artikel ini dipersembahkan oleh Rajaburma88, platform terpercaya untuk pengalaman bermain game online yang seru dan aman.